Mengenal Cagar Budaya
Oleh: Teguh Hidayat
(Disampaikan
dalam Sosialisasi Cagar Budaya yang diselenggarakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 29 Agustus 2017)
Cagar Budaya (CB)
adalah istilah hukum (dan politik) untuk menyebut data arkeologi, peninggalan
masa lalu, peninggalan purbakala, sumberdaya akeologi, dan seterusnya. Cakupan
CB sebenarnya sangat luas dan dapat dilihat dari berbagai aspek intrinsik,
antara lain:
·
aspek rentang
waktu yang meliputi CB masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, dan masa
Islam/kolonial;
·
aspek wujud
meliputi CB bergerak dan tidak bergerak;
·
aspek
ketersediaan meliputi CB tunggal dan multi atau kompleks;
·
aspek keruangan
meliputi CB insitu dan tidak insitu;
·
aspek locus
meliputi CB dalam kerangka
ruang seperti pegunungan, perkotaan, pantai, dsb;
·
aspek
ketersediaan informasi meliputi CB telah memiliki informasi yang mendalam,
sedang, atau seadanya;
·
aspek tingkat
pengelolaan, seperti CB temuan baru, sedang diteliti, dalam tahap pemugaran,
telah dipugar, CB telah menjadi ODTW;
·
serta aspek-aspek
lain yang melekat pada BCB seperti aspek kepemilikan, authentisitas, hukum,
keutuhan, ancaman kelestarian, stakeholders, dsb.
Begitu luas dan
kompleks memang rentang aspek intrisik di dalam CB sehingga kompleks pula
proses penanganannnya, yang jika disederhanakan meliputi pelindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan. Khusus untuk aspek
pemanfaatan, Cleere (1989: 9-10) menjelaskan bahwa manajemen sumberdaya
arkeologi memiliki tiga tumpuan pemanfaatan, yaitu:
·
akademik,
berkaitan dengan
pemanfaatan CB untuk kegiatan ilmiah atau penelitian dan pengembangan ilmu;
·
ideologik
yang terkait erat
dengan dunia pendidikan (edukasional) antara lain untuk mewujudkan “cultural
identity”; dan
·
ekonomik yang berkaitan dengan keuntungan
ekonomik misalnya melalui kepariwisataan
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar
Budaya, Pasal 1 di jelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat
kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar
Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air
yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui
proses penetapan.
Jenis Cagar Budaya
1.
Benda Cagar
Budaya
benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun
tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau
sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah
perkembangan manusia.
2.
Bangunan
Cagar Budaya
susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda
buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak
berdinding, dan beratap.
3.
Struktur Cagar
Budaya
Susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan
manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam,
sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
4.
Situs Cagar
Budaya
Lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai
hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
5.
Kawasan Cagar
Budaya
Satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau
lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang
khas.
Kriteria Cagar Budaya
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan
sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya
apabila memenuhi kriteria :
a.
Berusia 50 (lima
puluh) tahun atau lebih;
b.
Mewakili masa
gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c.
Memiliki arti
khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d.
Memiliki nilai
budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
Objek Cagar
Budaya
Merupakan semua tinggalan
arkeologi yang berasal dari masa awal kehidupan manusia sebelum munculnya
budaya tulis hingga pada masa lima puluh tahun lalu. Objek tersebut dapat
dikategorikan menjadi:
1.
Objek periode Prasejarah
Merupakan objek
yang berasal dari mulai adanya unsur kebudayaan pertama dan berakhir pada saat
manusia mulai mengenal tulisan. Masa berakhirnya masa prasejarah berbeda-beda
bagi setiap suku bangsa karena perbedaan waktu dalam mengenal tulisan.
Peninggalan arkeologi
pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu peninggalan bergerak dan
peninggalan tidak bergerak. Untuk periode prasejarah, yang termasuk peninggalan
bergerak antara lain alat-alat batu, perhiasan batu, peralatan dari tulang,
perhiasan dari kulit kerang, dan gerabah. Sementara itu peninggalan tak
bergerak antara lain bangunan megalitik dan gua hunian. Daerah yang memiliki
banyak tinggalan prasejarah di Sumatera Barat terdapat di Mahat, Limapuluh Kota
yang berupa batu menhir. Di Indonesia pembabakan jaman prasejarah dibagi
berdasarkan atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pendukungnya. Pembabakan
tersebut terdiri atas:
a.
Masa berburu dan
meramu makanan tingkat sederhana (Paleolitik)
b.
Masa berburu dan
meramu makanan tingkat lanjut (Mesolitik)
c.
Masa bercocok
tanam (Neolitik)
d.
Masa perundagian
2.
Objek periode Klasik
Merupakan objek yang dimulai sejak dikenalnya tulisan sampai masuknya pengaruh
kebudayaan Islam di Indonesia. Bidang kajian ini dimulai sejak abad ke-4 Masehi
dengan mengacu pada prasasti Yupa yang ditemukan di Kalimantan Timur sampai
runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada rentang waktu itu di
Nusantara memang berkembang kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan India.
Kebudayaan ini bernafaskan agama Hindu dan Buddha. Adapun cagar budaya yang berasal dari masa klasik antara lain
candi, petirtaan, arca, prasasti, keramik, mata uang, dan berbagai artefak lain
yang berasal dari kurun waktu abad ke-4-15 Masehi.
Untuk wilayah Sumatera Barat objek ini bisa dijumpai di Kabupaten
Dharmasraya, seperti Candi Padangroco, Candi Pulausawah, dan Candi Awang
Maombiak. Di Kabupaten Tanah Datar banyak ditemukan prasasti-prasasti yang
dikeluarkan oleh Raja Adityawarman, seperti Prasasti Pagaruyung, Prasasti
Kuburajo, dan Prasasti Rambatan. Di Kabupaten Pasaman dapat dijumpai tinggalan
candi seperti Candi Tanjung Medan, Candi Koto Rao, dan Candi Pancahan. Provinsi
Riau juga memiliki candi yang cukup dikenal yaitu Candi Muara Takus. Sedangkan
di Provinsi Kepulauan Riau ada Prasasti Pasir Panjang di Tanjungbalai Karimun.
3.
Objek periode Islam, yaitu objek yang berasal
sejak pengaruh kebudayaan Islam, seperti: nisan, masjid, naskah kuno dan lain
sebagainya.
Arkeologi Islam mempelajari
hal-ihwal berbagai kerajaan atau kesultanan yang pernah ada di bumi Nusantara. Tinggalan ini
yang ada di Sumatera Barat, Riau, maupun Kepulauan Riau relatif masih banyak,
seperti Masjid Kayu Jao di Solok, Masjid Enam Puluh Kurang Aso di Solok Selatan,
Masjid Lima Kaum di Batusangkar, dsb. Di Riau terdapat Istana Siak, Makam
Raja-Raja Kota Lama di Rengat, Masjid Tua Air Tiris, dsb. Di Kepulauan Riau
tinggalan ini banyak terdapat di Pulau Penyengat, Tanjungpinang dan Daik,
Lingga.
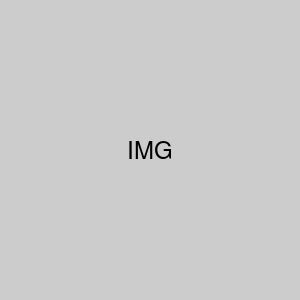
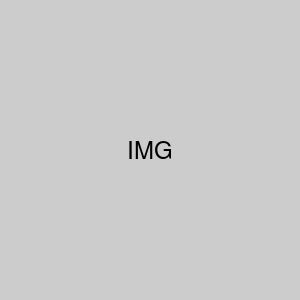
4.
Objek periode Kolonial, yaitu objek yang
berasal sejak pengaruh budaya Eropa, seperti: benteng, gereja, rumah kolonial
dan lain sebagainya. Berbagai pengaruh
itu berasal dari negara-negara Belanda, Portugis, Inggris, Cina, dan lain-lain
yang pernah mengisi perbendaharaan sejarah kuno Indonesia. Beberapa objek
yang ada di Sumatera Barat banyak tersebar di sekitar Kawasan Muaro seperti
rumah-rumah tua dan klenteng dan Bukittinggi, seperti Jam Gadang dan Gua
Jepang.
Mengapa Harus Dilestarikan
n Sifat Cagar
Budaya:
ü Finite (terbatas bentuk, jumlah, dan jenisnya), karena merupakan peninggalan
masa lalu dan proses waktu yang sudah ratusan tahun berlangsung sehingga tidak
banyak yang masih bertahan hingga sekarang ini.
ü
Langka dan tidak
terbarukan (unrenewable), artinya
bahwa cagar budaya tidak dapat
ditukar dengan benda lain, sekalipun yang sejenis.
ü Unik, dengan nilai-nilai historis,
arsitektur, maupun ekologi yang khas sehingga menjadi daya tarik untuk
dikunjungi para wisatawan. Nilai histories yang sarat akan makna, perlu dan
harus dipahami oleh bangsa ini dari generasi ke generasi. Sebab, dalam nilai
histories tersebut terkandung pula nilai-nilai lain yang dapat mengajak kepada
generasi muda untuk bisa bersikap dan bertindak secara positif, seperti
misalnya sikap kepahlawanan, cinta tanah air, rasa kesatuan dan persatuan,
serta berbudi pekerti yang luhur.
ü Mudah rusak (fragile)
ü Mudah mengalami kerusakan dan pelapukan (degradable)
n Nilai Penting:
ü Keilmuan :
penting untuk penelitian keilmuan
ü Sejarah : bukti peristiwa sejarah penting
ü Etnis
: identitas kelompok etnis
ü Publik : pendidikan masyarakat, fasilitas
ü Ekonomi : rekreasi, daya tarik wisata
ü Estetis : karya seni, arsitektural
ü Sosial : mewujudkan
solidaritas sosial
Pengertian
Pelestarian
Adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan
nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya,
yang terdiri dari
1.
Pelindungan
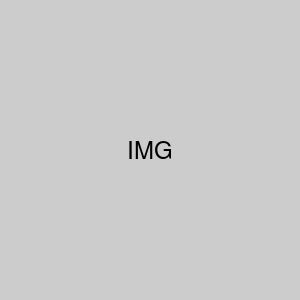 Upaya mencegah dan
menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara
Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya
Upaya mencegah dan
menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara
Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya
2.
Pengembangan
Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya Serta pemanfaatannya
melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi Secara berkelanjutan serta tidak
bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
3.
Pemanfaatan
Pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan
rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
Setelah cagar
budaya berhasil dilestarikan, maka tahap akhir dari sistem pengelolaannya
adalah pemanfaatannya. Cagar budaya tidak hanya untuk kepentingan lembaga
tertentu, akan tetapi dapat dimanfaatkan pula oleh berbagai kepentingan, antara
lain:
1.
Scientific research, artinya bahwa
cagar budaya tidak hanya untuk memenuhi kepentingan ilmu arkeologi ataupun
lembaga arkeologi dan purbakala, tetapi berbagai disiplin lain dapat pula
memanfaatkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Contoh: cagar budaya tidak bergerak seperti candi, masjid, dan gereja kuno
dapat pula dijadikan kajian dan obyek penelitian para arsitek maupun ahli
teknik lainnya.
2.
Creative arts, bahwa cagar
budaya dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi bagi para seniman,
sastrawan, penulis, dan fotografer dengan memanfaatkan obyek tersebut sebagai
obyek kreativitasnya.
3.
Education, cagar budaya
mempunyai peranan penting dalam pendidikan bagi pelajar dan generasi muda,
terutama dalam upaya menanamkan rasa bangga terhadap kebesaran bangsa dan tanah
air.
4.
Recreation and tourism, pemanfaatan
cagar budaya yang paling umum dan nyata ialah sebagai obyek wisata yang dikenal
dengan wisata budaya. Lebih-lebih untuk obyek cagar budaya yang berada pada
lingkungan alam yang menarik akan memiliki nilai tambah dan daya tarik yang
tidak ditemukan di tempat lain.
5.
Symbolic representation, dimaksudkan
bahwa cagar budaya kadang-kadang dimanfaatkan sebagai gambaran secara simbolis
bagi kehidupan manusia. Misalnya Jam Gadang dapat dipahami sebagai symbol
Sumatera Barat umumnya dan Kota Bukittinggi khususnya.
6.
Legitimation of action, banyak para
pejabat dan orang-orang yang berduit, setelah mendapatkan kedudukan atau
kekayaan, mereka kadang-kadang berusaha untuk dapat memiliki atau menguasai
cagar budaya tertentu agar dapat meyakinkan kepada masyarakat umum tentang
kesuksesan dirinya dan untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi.
7.
Social solidarity and integration, cagar budaya
yang berupa makam cikal-bakal suatu desa/wilayah tertentu dapat mewujudkan
suatu motivasi solidaritas sosial dan integrasi yang kuat dalam suatu
masyarakat. Pada saat-saat tertentu para ahli waris yang merasa keturunan cikal
bakal tersebut mereka menziarahinya, maka pada sat itulah akan muncul kesadaran
di antara mereka.
8.
Monetary and economic gain, cagar budaya
yang telah dimanfaatkan sebagai obyek wisata budaya, akan mendatangkan
keuntungan terutama bagi masyarakat di sekitar obyek. Pemerintahpun akan
mendapatkan pemasukan sebagai pendapatan asli daerah yang berasal dari pungutan
retribusi.
________________
*)Kasi Pelindungan,
Pengembangan, dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar
Sumatera Barat
Alamat Kantor:
Jl. Sultan Alam
Bagagarsyah, Pagaruyung, Batusangkar

Komentar
Posting Komentar